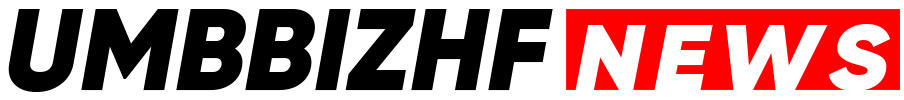Catatan: Artikel ini tidak mencerminkan pendapat pribadi penulis dan pendapat Dewan Redaksi UMBBIZHF NEWS.
Dalam literatur sejarah perekonomian Indonesia, nama Sumitro Jojohadiksumo muncul sebagai pelita yang menerangi tanda-tanda industrialisasi dan nasionalisme ekonomi. Gagasannya untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama alat pengelolaan industri negara adalah sebuah kenegaraan ekonomi yang visioner.
Rekayasa sosial ekonomi dimana pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, namun menjadi aktor utama yang mengarahkan denyut perekonomian menuju cita-cita kebebasan dan keadilan sosial.
Namun setelah lebih dari setengah abad, ketika kita melihat wajah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), muncul kekhawatiran, yakni sudah sejauh mana kita melangkah dari mimpi besar tersebut, dan semangat pengelolaan Pancasila semakin melemah?
Memasuki tahun pertama pemerintahan Provo-Gibran, kekhawatiran ini mendapatkan momentum nyata karena pasangan kepemimpinan ini mewarisi lanskap yang kompleks, terjebak di antara dua logika yang saling melengkapi: efisiensi perusahaan sebagai agen pembangunan dan tatanan sosial.
Di tahun penting ini, fokusnya adalah bagaimana memperluas visi “Indonesia Maju” ke dalam kebijakan yang konkrit. Akankah pemerintah kali ini memilih jalur pragmatis untuk mempercepat pelepasan BUMN yang “non-strategis” demi menjaga kesehatan keuangan? Atau malah mengambil langkah transformatif dengan memperkuat peran BUMN untuk membangun kedaulatan pangan, energi hijau, dan teknologi masa depan?
Tindakan nyata terhadap Danantara dan Otoritas Investasi Indonesia (INA) akan menjadi barometernya. Apakah Dantara akan diposisikan sebagai “KDB Indonesia” yang mempunyai amanah kuat untuk berinvestasi di sektor permodalan dan menatap ke depan? Atau akankah dia menjadi manajer portofolio yang menghindari risiko?
Begitu pula dengan INA: Apakah sektor tersebut akan menjadi sektor yang berisiko tinggi dan berisiko tinggi seperti semikonduktor dan farmasi, atau akankah tetap berlabuh pada aset infrastruktur yang sudah matang?
Di sisi lain, retorika penciptaan “nongyup ala Indonesia” perlu diuji dengan transformasi nyata, misalnya menghidupkan agro dan bulog menjadi tulang punggung logistik dan keuangan koperasi dan UMKM. Tahun pertama ini adalah momen yang menentukan: meletakkan dasar bagi grand design yang koheren dan berjangka panjang, independen dari siklus politik dan sejalan dengan semangat pancasila.
Struktur kepengurusan kami saat ini menggambarkan Dantara dan BP BUMN sebagai dua pilar, dengan pandangan yang saling tumpang tindih dan terkadang tidak konsisten. Pertanyaan mendasarnya adalah dari manakah sebenarnya inti pokok pembuatan suatu strategi?
Kebijakan yang tidak sinkron, seperti satu pihak membicarakan optimalisasi portofolio, sementara pihak lain menekankan kerja agen pembangunan, menimbulkan ketidakpuasan di tingkat direktur. Bumn telah menjadi raksasa yang tidak stabil: tidak cukup gesit di pasar bebas, namun tidak cukup fokus untuk mematuhi perintah negara.
Kehadiran INA yang diharapkan menjadi lompatan baru dalam pengelolaan kekayaan negara juga menimbulkan pertanyaan. Sebagai dana kekayaan negara, INA akan menjadi sarana investasi, mendatangkan modal dan meningkatkan nilai aset. Namun secara narasi strategis, INA masih terkesan bimbang: antara mengejar keuntungan ekonomi atau menjadi alat strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi jangka panjang.
Kekhawatiran muncul ketika mengkaji portofolio dan strategi INA jika hanya berfokus pada aset matang dengan arus kas stabil – seperti infrastruktur telekomunikasi dan tol yang penting bagi masa depan negara (seperti semikonduktor, farmasi atau teknologi ramah lingkungan), maka INA adalah tipikal manajer aset.
INA nampaknya gagal memainkan peran transformatifnya. INA harus menjadi katalis untuk menyasar sektor-sektor yang belum dapat dibebani tetapi memiliki nilai strategis yang tinggi, yang sejalan dengan semangat struktur inti industri Sumitro di negara ini.
Pembicaraan pembagian BUMN ke bidang-bidang yang “kurang strategis” juga menyisakan teka-teki. Di satu sisi, argumen mengenai efisiensi dan fokus negara pada sektor-sektor penting nampaknya masuk akal. Tapi, siapa yang mendefinisikan “kurang strategis”? Apakah tidak ada nilai strategis bagi hotel, perkebunan atau penyerapan lapangan kerja di sektor manufaktur tekstil, rantai pasok dalam negeri, dan pemerataan ekonomi?
Kita tidak perlu jauh-jauh menemukan contoh praktik terbaik Korea Selatan yang menghadirkan dua model sukses yang saling melengkapi: Korea Development Bank (KDB) dan Nonghyup (NH). KDB adalah contoh sempurna tata negara di daerah perbatasan, atau permulaannya
Melalui modal yang cukup, ia membiayai fase penelitian dan pengembangan yang berisiko tinggi, memperluas industrialisasi dari industri berat ke teknologi maju. KDB berhasil karena mandatnya jelas, yaitu bukan mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan membangun *National Champion* seperti Samsung dan Hyundai yang mampu bersaing secara global.
Sedangkan Nongyup (NH) menunjukkan kekuatan yang berbeda dengan koperasi pertanian yang dimulai pemerintah pada tahun 1960an, NH tumbuh menjadi raksasa keuangan dan logistik milik petani.
NH tidak hanya menyediakan modal, namun juga mendukung keseluruhan ekosistem pertanian: pemasaran, distribusi, logistik, asuransi dan perbankan. NH membuktikan bahwa organisasi yang lahir dari kebijakan negara dapat tumbuh secara mandiri, dikelola secara profesional dan mengakar pada landasannya.
Bayangkan jika Indonesia memiliki “KDB ala Indonesia” yang fokus pada industri masa depan dan NH “NH” ala Indonesia yang mengintegrasikan dan memperkuat koperasi dan UMKM di sektor pangan, kelautan, dan kerajinan.
Masalahnya, kita sering terjebak pada solusi paling sederhana: menggabungkan merger yang dipaksakan tanpa penyelarasan strategis dan analisis mendalam terhadap budaya organisasi hanya akan melahirkan birokrasi yang malas. Persoalan mendasarnya adalah kejelasan visi bahwa kita harus merasionalkan BUMN berdasarkan peta jalan industri Indonesia, bukan sekedar angka
Lantas, bagaimana mendamaikan situasi perekonomian Indonesia di tengah angin globalisasi dan kepentingan modal global? Jawabannya mungkin terletak pada filosofi dasar ekonomi kita: Pancasila kalau Korea Selatan punya Saimaul Ondong yang artinya Gotong Ryong, maka Indonesia punya Pancasila yang merupakan awal dari semangat akumulasi.
Pertama, Indonesia membutuhkan grand design yang terpadu dan transparan sebagai peta navigasi yang menguraikan secara jelas peran Bumn, Danantara, dan Ina dalam Orkes Pembangunan Nasional. Peta ini harus melampaui visi lima tahun, komitmen jangka panjang terhadap negara, yang tidak dapat digantikan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
Kedua, BUMN harus kembali berperan sebagai perusahaan pelayanan publik. Orientasi profit itu penting, tapi bukan tujuan utama, sedangkan profit adalah oksigen kelangsungan hidup dan pembangunan, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.
Kinerja direksi BUMN tidak hanya dapat diukur dari rasio keuangan, tetapi juga kontribusinya terhadap rantai pasok dalam negeri, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dan penyediaan barang/jasa strategis yang terjangkau.
Ketiga, Dantara perlu berani menjadi pionir untuk menjadi rumah impian besar teknologi Indonesia dengan mengambil risiko dalam melakukan investasi strategis demi masa depan negara.
Keempat, Indonesia perlu menciptakan “nongyup Indonesia”. Daripada mengalihkan BUMN ke sektor riil untuk membentuk koperasi yang kurang strategis atau merah putih yang tidak memiliki visi yang jelas, mengapa tidak diubah menjadi koperasi modern milik petani, nelayan, dan pengusaha kecil dengan dukungan perbankan dan logistik dari negara pada tahap awal? Ini adalah bentuk sebenarnya dari Pasal 33 yang artinya lebih dari sekedar pembagian
Perekonomian Indonesia saat ini dengan kesenjangan dan ketergantungan terhadap impor pada sektor-sektor strategis menunjukkan bahwa kita semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Kita terjebak dalam pragmatisme jangka pendek dan kehilangan kompas strategis jangka panjang seperti Pancasila. (miq/miq)