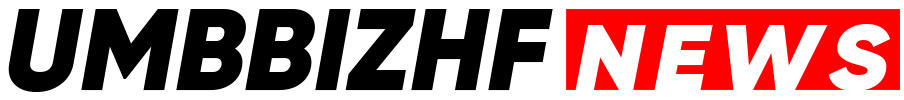DISCLAIMER: Artikel ini adalah opini penulis dan tidak mencerminkan opini CNBCINDON.com.
Belakangan ini masyarakat Indonesia semakin marah bukan hanya karena kebijakannya, tapi juga karena cara masyarakatnya berkomunikasi. Pembicaraan yang seharusnya berjalan tenang justru sarat dengan kontradiksi, hingga jarak antara pemimpin dan rakyat semakin jauh. Hal ini menunjukkan betapa sadarnya keterampilan komunikasi masyarakat negara tersebut.
Dalam teori komunikasi politik terdapat dua sumber yang dapat dijadikan pedoman, yaitu teori empati dan teori malam.
Teori omong kosong menekankan pentingnya komunikasi memahami pikiran khalayak. Artinya, pemimpin bukan saja kurang pengetahuannya, tetapi juga merasa cemas, penuh harapan, dan visioner terhadap rakyatnya.
Saat ini, teori rasisme menekankan bahwa hubungan yang baik dibangun di atas hal-hal seperti orang yang lebih tua, asal usul, asal usul, agama, agama, perasaan, dan pengalaman, dan pengalaman, dan pengalaman, dan pengalaman, dan pengalaman, dan hal-hal yang pernah dijalani. Ide utamanya, semakin sederhana pesannya.
Sayangnya, banyak orang yang mengabaikan kedua hal tersebut. Kita masih ingat pemberitaan pejabat yang menasihati masyarakat untuk “Makan singkong saat harga beras mahal”, atau banyak komentar lain yang menjadi kritik masyarakat.
Alih-alih melakukan penipuan, gagasan seperti ini malah menambah luka dan memperkuat persepsi bahwa pejabat hidup di gajah, jauh dari memukuli rakyatnya. Komunikasi yang gagal memahami empati dan mengabaikan kubu justru akan semakin memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan warga.
Lebih dari sekedar berbicara, komunikasi yang efektif memerlukan mendengarkan. Teori yang diajukan menekankan bahwa komunikasi merupakan jalan dua arah. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak hanya mengubah pesan, tapi dia mengambil minat masyarakat.
Bagaimanapun, dalam realitas dialog yang sukses, mendengarkan suara masyarakat adalah bagian terpenting dalam membangun agama politik. Tanpa mendengarkan, Komunikasi masuk ke Monogue, kehilangan Sentuhan, dan menutup tempat kasih sayang.
Tulisan ini bukan sekadar mengkritisi bahasanya, namun hanya mengingatkan kita bahwa media sosial adalah alat politik yang memutuskan untuk membocorkan rahasia politik yang memutuskan untuk membocorkan rahasia. Orang menjadi agen bukan hanya karena tindakan mereka, tapi juga karena cara mereka “diberitahu”.
Kata-kata empati dapat mengatasi rasa frustrasi, bahkan dalam situasi sulit. Sebaliknya, komentar yang tidak pantas dapat menimbulkan kemarahan meskipun tujuan yang diberikan bermaksud baik. Komunikasi bukanlah tampilan kata-kata, melainkan jembatan antar hati. Kata-kata penuh kasih sayang, yang dibangun secara harmonis, dan diberikan kepada kita melalui program mendengarkan, akan berhasil dan efektif.
Seperti yang pernah dikatakan Stephen R. Cogot, penulis 7 Ways to Success: “Kebanyakan orang tidak mendengarkan.”
Oleh karena itu, sudah saatnya publik figur di Indonesia memperbaiki cara berkomunikasinya. Para pemimpin harus berhenti berbicara dari atas, dan mereka yang berada jauh harus mulai berbicara tentang hati rakyat. Berjejaring bukan satu-satunya rencana Anda, namun akan menjadi bagian dari upaya untuk mempercayai, melakukan pendekatan, dan berbagi makna.
Seperti yang pernah diingatkan Nelson Mandela kepadanya, “Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang mereka pahami, maka mereka pun akan mengerti.”
Pesannya sederhana namun menarik: tanpa empati, bahasa seorang pemimpin akan kehilangan makna, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan diri. Ingat, pemimpin yang tidak hadir akan kehilangan rakyatnya jauh sebelum ia kehilangan jabatannya. (Miq / Miq)