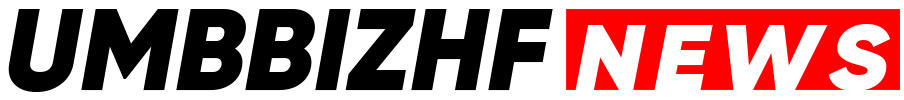Catatan: Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Dewan Redaksi UMBBIZHF NEWS.
Jika dulu musuh utama bangsa adalah penjajahan dan penindasan negara asing, kini musuh terbesar datang dari bangsa Indonesia sendiri. Musuh ini terwujud dalam keserakahan para elite yang memperkaya diri dan sekaligus membuat masyarakat terjebak dalam rantai kemiskinan struktural.
Salah satu gambaran sebenarnya dari ketimpangan ini adalah banyaknya jabatan yang dipegang oleh pejabat publik, korupsi besar-besaran yang tidak pernah sepenuhnya diberantas oleh hukum, penjahat kerah putih yang terlibat dalam kejahatan, dan pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan ambisi pribadi. Artinya, tindakan tersebut tidak lagi hanya memperlebar kesenjangan kekayaan, tetapi juga merusak landasan moral pemerintah.
Di saat jutaan orang menuntut pekerjaan, tercekik oleh tingginya biaya kebutuhan dasar dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, para pejabat sibuk menimbun jabatan, gaji dan fasilitas. Di tengah meningkatnya angka pengangguran pendidikan, PNS yang seharusnya menjadi PNS malah menjadi “PNS”.
Perlukah pelayanan publik memiliki tanggung jawab moral dan nilai sakral yang tidak layak dirusak oleh keserakahan? Jadi bagaimana masyarakat bisa mempercayakan masa depan mereka kepada pejabat yang menggunakan jabatannya untuk perdagangan dan gengsi, bukan pelayanan? Pertanyaannya, apakah kita masih mau berpura-pura tidak melihat fakta bahwa kemiskinan struktural di negeri ini semakin parah?
Dua Wajah Kemiskinan Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook pada April 2025 mengindikasikan bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 171,8 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan global. Sebaliknya, versi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional per September 2024 hanya 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Mengapa hal ini sangat tidak setara?
Perbedaan ini terletak pada metodologinya. Bank Dunia menggunakan pendekatan paritas daya beli (PPP) dengan tiga kategori, yakni kemiskinan ekstrim di bawah US$2,15 per hari, negara berpendapatan menengah bawah di bawah US$3,65, dan negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia di bawah US$6,85. Sementara itu, BPS mengukurnya berdasarkan pendekatan Biaya Kebutuhan Pokok (CBN), yaitu besarnya pengeluaran minimal untuk kebutuhan pangan (kurang lebih 2.100 kilokalori per hari) dan non pangan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Namun pendekatan ini seringkali tidak mencerminkan realitas daya beli masyarakat yang sebenarnya dalam hal inflasi dan perbedaan harga antar daerah. Selain itu, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi dasar BPS dilakukan dua kali setahun dan sangat bergantung pada laporan konsumsi yang seringkali tidak mencerminkan kondisi rumah tangga yang “terlambat”.
Warisan Kemiskinan Jika dulu kita mengenal istilah kemiskinan absolut atau kemiskinan relatif, kini kemiskinan di Indonesia telah berubah menjadi kemiskinan kronis, yaitu keadaan dimana kemiskinan diturunkan dari generasi ke generasi. Bayangkan, jika seorang anak lahir dari keluarga miskin, besar kemungkinan ia akan tumbuh miskin, kecuali ada intervensi kebijakan struktural yang “radikal dan demi kepentingan keadilan sosial”.
Sekali lagi saya ingin mengajak anda untuk berpikir, bayangkan, sejak dalam kandungan, anak-anak dari keluarga miskin merasakan ketimpangan. Sang ibu kekurangan gizi, tidak mampu membayar layanan kesehatan pra melahirkan, atau tinggal di lingkungan yang tidak memadai. Mereka tidak hanya mewarisi kemiskinan ekonomi, namun juga kurangnya akses terhadap pendidikan, sanitasi dan pangan dalam sebuah lingkaran setan yang sulit diputus jika negara memperhatikannya.
Seandainya mereka berbicara dari dalam rahimnya, mungkin mereka akan menangis: “Tolong, jangan melahirkan saya. Seharusnya saya dilahirkan agar saya tidak menderita. Saya khawatir dengan keadaan keuangan orang tua saya yang masih menangis dalam kemiskinan. Lalu bagaimana saya bisa memahami kebahagiaan itu? Tolong, tunda kelahiran saya dari rahim ibu saya.”
Tangisannya benar-benar membuatku menangis saat dia menggambarkan adegan ini. Seruan itu tidak akan didengar oleh mereka yang duduk di menara gading kekuasaan. Namun protes tersebut telah mengakibatkan kematian anak-anak karena kekurangan gizi, anak-anak putus sekolah, dan remaja yang masa depannya hilang karena mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk berkembang. Ada kejadian serupa di sekitar kita masing-masing.
Tangisan-tangisan yang tidak terdengar di ruang rapat para pengambil keputusan politik, yang lebih mementingkan perdebatan mengenai insentif dan posisi strategis dibandingkan tangisan anak-anak yang lahir tanpa masa depan. Suara yang tak mampu menembus tembok istana, namun terdengar di bawah setiap jembatan, rumah gubuk, dan pusat kesehatan yang kehabisan vitamin.
Tangisan anak itu seolah berkata: “Aku juga ingin tertawa bahagia seperti anak-anak penguasa dan elit negeri ini. Aku juga ingin menikmati susu segar dan tempat tidur yang hangat seperti anak-anak yang lahir dari rahim kekuasaan. Aku juga ingin bersekolah di tempat terbaik, mainan, makanan sehat dan pelukan, tanpa ibuku yang tidak ingin tumbuh dewasa.”
Refleksi ini memungkinkan kita memahami bahwa kemiskinan bukan hanya soal angka, bukan hanya soal tidak cukup makan atau tidak bersekolah. Itu dikeluarkan atas dasar keadilan. Mimpi yang terputus sebelum sempat tumbuh. Ini tentang bagaimana suatu sistem secara diam-diam dapat menciptakan kemiskinan baru, namun di tempat lain, seperti di gedung-gedung tinggi dan salon-salon mewah, anak-anak dilahirkan untuk menemukan kedamaian dan kekuasaan.
Kemiskinan bukan hanya soal statistik di lembar laporan kementerian. Ini adalah situasi kehidupan nyata yang buruk dan mematikan harapan. Banyak masyarakat yang terjebak dalam kendala struktural yang membuat mereka tidak mungkin keluar dari kemiskinan, karena mereka terikat oleh sistem yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Keadilan sosial kini hanya menjadi sebuah kata.
Dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional yang baru saja berlalu, kita harus memikirkan: pantaskah kita mengucapkan “Selamat”? Atau haruskah saya mengatakan “simpan”? Bebaskan buruh dari sistem perburuhan yang menindas. Membebaskan dunia pendidikan dari komersialisme. Menyelamatkan generasi muda dari jebakan kemiskinan struktural.
Untuk memutus rantai ketimpangan kita perlu beranjak dari paradigma lama yang hanya mengikuti angka statistik pertumbuhan ekonomi tanpa menyentuh substansi permasalahan sosial. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penurunan angka kemiskinan, atau peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang penting, namun tidak pernah cukup jika di balik itu semua masih ada ketidakadilan struktural tersembunyi yang menindas rakyat kecil.
Sudah saatnya kita bergerak menuju transformasi sosio-ekonomi yang benar-benar signifikan, yang tidak hanya menunjukkan wajah pembangunan di atas kertas, namun membawa kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Reformasi kebijakan sosial harus menjadi pusat pembangunan nasional. Artinya, setiap kebijakan publik tidak boleh lagi berpihak pada segelintir elit politik dan ekonomi, namun harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Hal ini mencakup keberanian untuk mengatur kembali distribusi sumber daya nasional agar lebih adil, menghilangkan praktik jabat ganda yang melemahkan akuntabilitas, dan memperkuat sistem jaminan sosial yang non-diskriminatif.
Pendidikan harus dihadirkan sebagai pintu keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan sekadar formalitas administratif yang sulit dijangkau anak-anak di daerah terpencil. Kesehatan juga harus dilihat tidak hanya sebagai pelayanan medis, namun sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang.
Kemiskinan struktural tidak bisa lagi ditangani dengan pola pikir filantropis yang bersifat musiman – seperti bantuan sosial yang hanya diberikan sebelum pemilu atau ketika krisis sedang mendesak. Solusinya harus berupa reformasi sistem yang tidak setara: redistribusi tanah dan akses terhadap perekonomian produktif, terhadap penciptaan lapangan kerja yang layak dan bukan hanya upah rendah. Meskipun negara ini masih sibuk mengabadikan narasi-narasi palsu dan perayaan-perayaan kosong, gambaran kemiskinan akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bangsa ini harus jujur pada dirinya sendiri: apakah kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun itu benar-benar milik seluruh rakyat, atau hanya segelintir orang saja yang menikmati keistimewaan kekuasaan dan kekayaan?
Jika tidak segera ditindaklanjuti, anak-anak yang lahir dari rahim kemiskinan akan mengalami kerusakan struktural sejak pertama kali mereka melihat dunia. Mereka tumbuh dengan akses terbatas, kesempatan yang tidak setara, dan masa depan yang ditentukan oleh takdir, namun sebenarnya ditentukan oleh pilihan kebijakan negara.
Sebenarnya saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar, karena menulis kalimat ini saja sudah membuat saya berlinang air mata. Terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agenda reformasi sosial ekonomi bukan sekedar jargon pembangunan, namun merupakan tuntutan moral dan politik yang tidak dapat ditunda lagi.
Kita memerlukan keberanian politik untuk membongkar struktur ketidakadilan, komitmen para teknokrat untuk merancang kebijakan inklusif berdasarkan data, dan koordinasi birokrasi untuk melaksanakannya tanpa korupsi atau manipulasi. Hanya dengan cara inilah kita dapat benar-benar mengangkat masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan, dan menjadikan kemerdekaan sebagai aset kolektif, bukan sekedar simbol tahunan yang tidak berarti. (miq/miq)