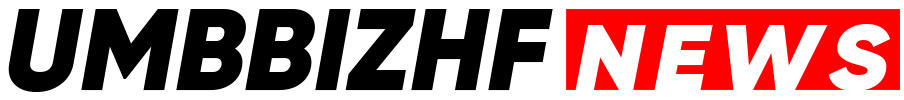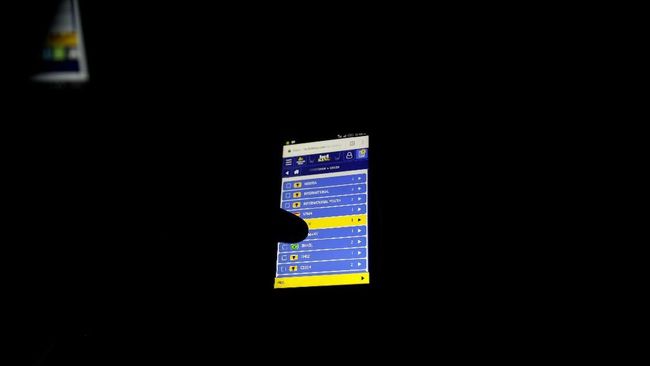Catatan: Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Dewan Redaksi UMBBIZHF NEWS
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembatalan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat yang kaya akan keanekaragaman hayati laut yang terkenal di dunia, masyarakat melihatnya sebagai langkah positif untuk menjaga lingkungan dan keindahan di sana.
Namun respon di lapangan justru menunjukkan sisi lain yang lebih kompleks. Penambang lokal menghalangi wisatawan untuk masuk dan menuntut penjelasan mengenai nasib finansial mereka. Sementara Pulau Gag masih memiliki IUP sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan tersebut.
Kasus ini mengungkap rumitnya pengurusan izin pertambangan nasional.
Perubahan Peraturan Pertambangan Sistem perizinan pertambangan di Indonesia telah mengalami evolusi yang panjang dan tidak selalu linier. Dari era Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), ketika kepentingan asing mendominasi jangka panjang dan rendahnya daya tawar pemerintah, kita beralih ke Sistem Perizinan Pertambangan (IUP) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
Namun desentralisasi pasca reformasi justru menimbulkan fenomena “banjir izin” dari pemerintah daerah yang tidak selalu didasarkan pada perencanaan daerah dan kajian lingkungan hidup. Peraturan yang tumpang tindih menjadi permasalahan yang serius.
UU Kehutanan melarang penambangan terbuka di hutan lindung, UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melarang penambangan di pulau-pulau kecil, dan UU Lingkungan Hidup mewajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Namun ketiga hal ini sering diabaikan karena tidak terkoordinasi.
Negara berupaya memperbaiki keadaan tersebut dengan melakukan pengecekan mineral dan kolagen (UU Nomor 3 Tahun 2020) dan melalui PP Nomor 96 Tahun 2021 dengan memperkuat sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Namun harmonisasi peraturan perundang-undangan belum optimal.
Pencabutan izin: sebab dan akibat Peningkatan terbesar dalam pengawasan izin terjadi pada awal tahun 2022, ketika Presiden Joko Widodo mencabut lebih dari 2.000 izin pertambangan yang dianggap tidak aktif, bermasalah, atau berada di kawasan lindung. Langkah ini disambut baik, namun juga menimbulkan tantangan hukum.
Sekitar 585 izin dikembalikan kepada pemegangnya setelah proses verifikasi. Kurangnya transparansi dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pencabutan izin membuat banyak pihak mempertanyakan legalitas proses tersebut.
Pembatalan izin juga menimbulkan pertanyaan hukum: apakah perusahaan pertambangan berhak mendapat kompensasi? Jawabannya rumit. Menurut undang-undang nasional, kompensasi tidak dibayarkan jika perusahaan dianggap lalai atau melanggar aturan.
Namun demikian, investor asing masih terbuka untuk menggugat pemerintah Indonesia melalui proses arbitrase internasional berdasarkan perjanjian investasi bilateral. Hal ini mungkin berdampak pada reputasi hukum dan iklim investasi kami. Dalam konteks Raja Ampat, pencabutan keempat IUP tersebut bertujuan untuk melindungi ekosistem laut di Geopark Raja Ampat yang baru-baru ini mendapatkan status Global Geopark UNESCO. Namun kegagalan dalam mengkomunikasikan dan memberikan alternatif ekonomi kepada masyarakat lokal dapat menciptakan gesekan sosial yang lebih kompleks.
Tanpa kerja sama, keputusan pemulangan dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal yang berkepanjangan.
Menuju administrasi yang adil dan berkelanjutan Diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk meningkatkan manajemen operasi pertambangan. Pertama, audit nasional terhadap seluruh perusahaan IUP yang aktif harus dilakukan secara terbuka dan inklusif dengan melibatkan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Audit ini mencakup aspek administrasi, lingkungan, sosial dan kepatuhan desain fisik.
Kedua, pemerintah harus menetapkan izin dan prosedur pencabutan izin yang adil. Kejelasan dasar hukum, urutan langkah, batas waktu penyelesaian, dan hak keberatan harus dijamin agar tidak timbul ketidakpastian hukum.
Ketiga, kebijakan pertambangan ke depan harus didasarkan pada perspektif bentang alam dan daya dukung wilayah. Definisi zona pertambangan tidak boleh berdiri sendiri, namun harus konsisten dengan perlindungan ekosistem, hak masyarakat adat dan potensi ekonomi lainnya seperti pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat setempat, karena perencanaan merupakan kunci keberhasilan.
Keempat, negara harus memperkuat jaminan restorasi dan daur ulang pascatambang serta memastikan bahwa sumber daya dikelola secara bertanggung jawab. Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun alternatif ekonomi bagi wilayah bekas pertambangan yang berbasis sumber daya lokal.
Terakhir, mekanisme koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan harus diperkuat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah kota harus secara rutin duduk bersama dalam forum lintas sektoral yang permanen.
Forum ini dapat merumuskan kebijakan daerah, mengevaluasi perizinan secara berkala, dan berperan sebagai forum mediasi apabila terdapat potensi konflik perizinan. Dalam jangka panjang, pendekatan terpadu ini mencegah pemborosan sumber daya, mendorong investasi yang bertanggung jawab, dan memastikan perlindungan ekosistem yang lebih kuat.
Kasus Raja Ampat memberikan pelajaran bahwa sumber daya alam bukan sekadar komoditas ekonomi, namun bagian dari warisan bangsa. Untuk melindunginya diperlukan keberanian politik dan koherensi politik, serta empati terhadap masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertambangan.
Jika semua aspek tersebut diabaikan, maka pencabutan izin hanya akan menjadi kebijakan tambal sulam yang tidak menyelesaikan akar permasalahan. (miq/miq)